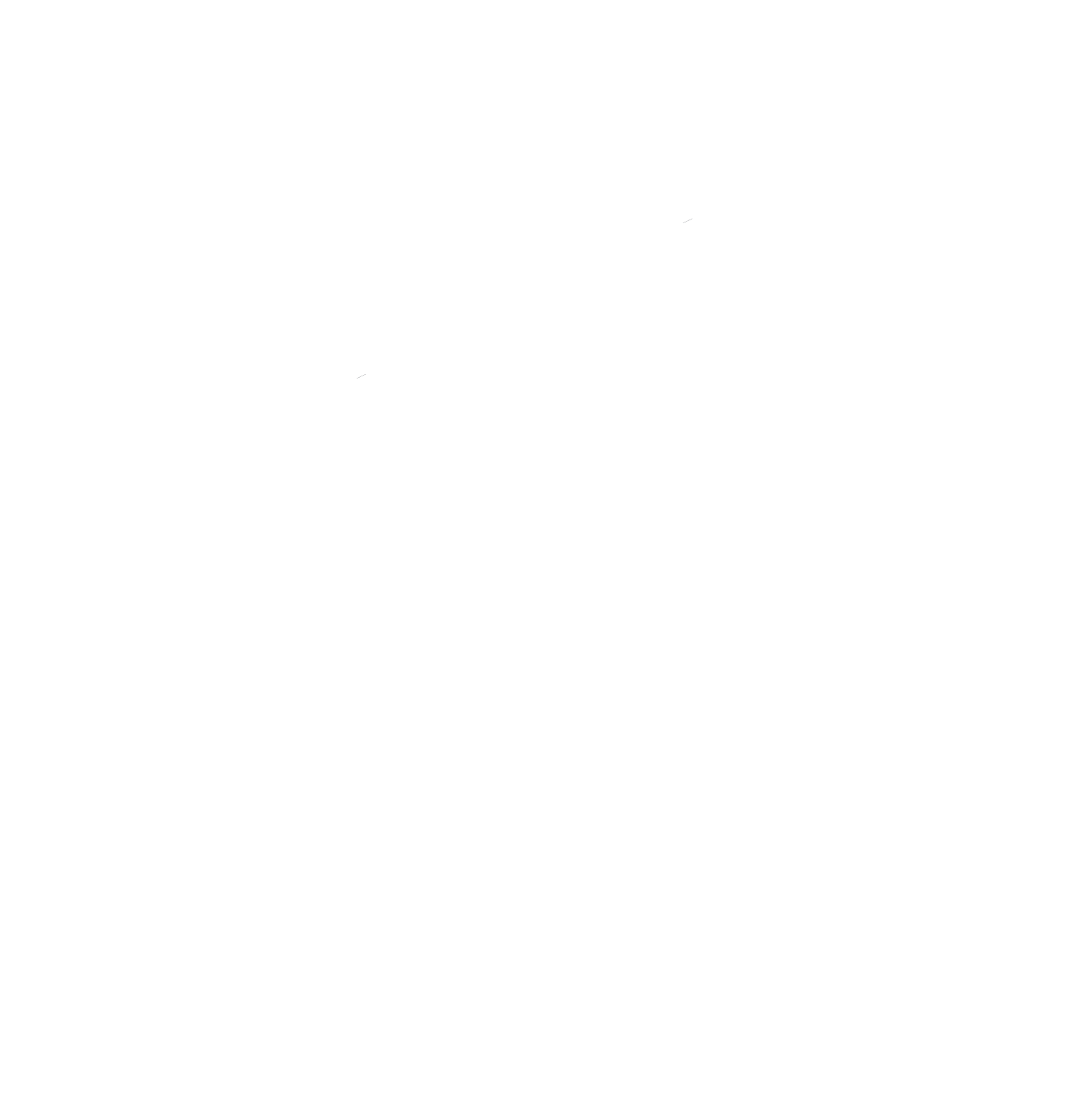“Saya mengajak mereka menanam kopi lagi, tanpa pupuk kimia, pestisida, dan panen petik merah. Itu saja!” tutur Putu Ardana membuka obrolan.
Pagi itu, ia mengenakan sandal gunung, celana kargo, dan kaos hitam, tampak santai. Penampilannya mengingatkan pada profil mahasiswa pecinta alam yang serba praktis dan siaga. Jangan membayangkan mahasiswa usia 20an. Tapi anggap aja sedikit agak lebih senior.
“Ya, seperti ini keseharian saya, menikmati hidup yang merdeka,” ujarnya dengan senyum ramah yang sumringah.
Rambutnya memang sudah memutih, tapi postur tubuhnya yang tegap memberi kesan sosok yang rajin beraktifitas fisik dan gesit, sat-set.
Putu Ardana adalah petani kopi di Desa Munduk, Buleleng, sekaligus penggerak upaya konservasi Kawasan Hutan (Alas) Mertajati Danau Tamblingan, Buleleng, Bali Utara.
Saya cukup beruntung, ia sudi menemani ngobrol di sela keasyikannya menyiapkan tunas kopi Arabica yang akan disambungkan ke pokok dahan robusta.
“Robusta perakarannya lebih baik dari Arabica. Hanya saja, robusta kurang produktif di wilayah tinggi seperti Munduk ini,” ujarnya.

Kami ngobrol di Café Don Biyu, kedai kopi miliknya yang sejak pandemi covid-19 terpaksa terhenti operasinya. Namun, tempat ngopi yang menghadap ke panorama nan indah lembah berlatar empat puncak gunung itu, masih menyimpan aura yang selaras dengan alam sekitar.
Kami duduk di bangku teras belakang yang terbuka. Pemandangan yang indah di depan kami ternoda oleh tiang tower provider telekomunikasi yang berdiri telanjang tak punya sopan-santun. Apa susahnya menambahkan sedikit ornament serupa daun, atau apa saja, yang setidaknya bisa menyamarkan rangka baja itu agar meminimalisir daya rusak ruang pandang. Ah, sudah lah.
Bangunan café di tepi lembah ini lumayan luas dan dibuat bertingkat dua. Lantai atas adalah ruang terbuka untuk menjemur hasil panen kopi. Ada tangga diagonal di sisi depan untuk naik ke sana.
Sedang di bawahnya ruangan kaca tembus pandang dengan jajaran meja dan bangku yang terbuat dari kayu solid. Kita mesti menaiki beberapa undakan tangga berlantai semen untuk memasuki tempat ngopi asyik ini.
Saya cuma berdecak dalam hati, sungguh orang ini diberkati tempat yang amat cantik. Apalagi kalau tanpa tower baja yang tidak sopan itu.
Suguhan pisang ketip rebus, yang masih mengepulkan uap panas, hadir bersama kopi tubruk panas. Terhidang pada sisi tengah meja, mengisi celah yang masih tersisa antara hamparan lembah hijau nan mempesona dan dingin udara pagi itu.
“Begini sarapan pagi saya, tidak harus nasi, cukup dua buah pisang ketip,” ujarnya sembari mempersilahkan menikmati kudapan dan kopi tubruk hasil kebun organiknya.
Kopi adalah suguhan yang umum bagi tamu di desa ini, sejak ratusan tahun yang lalu. Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Jawa untuk ditanam di Desa Munduk dan sekitarnya. Kawasan ini yang memang punya ketinggian diatas 900 mdpl dan iklim sangat ideal untuk jenis kopi arabica.
Kemungkinan dari tahun 1800an hingga 1970an, kopi Arabica masih menjadi komoditi utama kebun-kebun masyarakat Desa Munduk.
Menurut catatan literatur, pada 1825, hasil kebun kopi Bali sudah diekspor Belanda bersamaan dengan kopi dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Besar kemungkinan kopi dari Desa Munduk juga ikut serta.
Kala itu, setiap musim panen kopi, banyak warga dari Bali Selatan, seperti Ubud dan Gianyar, datang ke Munduk untuk bekerja sebagai pemetik kopi. Ramai pendatang disertai dengan munculnya banyak pedagang makanan musiman yang membuka lapak di Desa Munduk.
Sekarang justru sebaliknya. Karena gencarnya perkembangan pariwisata, Bali Selatan menjadi magnet yang lebih kuat.
Menurut Putu Ardana, di masa kecilnya, ia menyaksikan hampir setiap rumah di Desa Munduk punya halaman yang luas dan selalu menjadi tempat untuk menjemur kopi.
“Saking melimpahnya panen kopi, tingginya sampai sedengkul saya,” ujarnya menggambarkan seberapa tebal lapisan timbunan ceri kopi yang sedang dijemur.
Pada waktu itu, Desa Munduk sudah sangat identik dengan Kopi Bali.
Bahkan, di Munduk ada Pura Subak Abian yang sudah identik sebagai pura kopi. Karena setiap ada upacara tumpek wariga, warga masyarakat menghaturkan persembahan kepada Dewa Sangkara, yang dipercaya dalam tradisi Hindu sebagai pencipta tumbuh-tumbuhan. Kopi menjadi isian sesaji yang selalu ada.

Sejak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Putu Ardana cukup lama meninggalkan Munduk untuk melanjutkan sekolahnya. Tahun 1983, ia mesti rela meninggalkan desanya yang elok itu untuk kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Lulus kuliah, bersama teman-temannya membangun bisnis pembuatan t-shirt kreatif “Jaran Etnik”. Usahanya berkembang pesat, bahkan menjadi pionir munculnya bisnis serupa di Yogyakarta, juga daerah-daerah lain di Indonesia.
“Dagadu itu dulu nyetak kaosnya di Jaran Etnik,” ujarnya, menceritakan salah satu brand produsen kaos kreatif yang saat ini popular di Yogyakarta.
Meski bisnisnya saat itu sedang moncer, ia akhirnya memutuskan kembali ke Desa Munduk. Tapi ia tak menceritakan detail kenapa. Yang pasti tidak mudah meninggalkan teman dan bisnis yang lagi menanjak.
“Saya dipanggil Bapak pulang,” ucapnya singkat.
Menuruti panggilan sang ayah, ia pulang ke Munduk dan mulai menjadi petani. Berkutat dengan aktifitas kebun dan aneka kegiatan di masyarakat yang menjadi keseharian hidup orang Bali.

Munduk, secara adat, adalah bagian dari Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Yakni empat desa adat yang saling terkait; Munduk, Gesing, Umajero, dan Asah Gobleg.
Putu Ardana mulai mendapati ada banyak perubahan yang kian mencemaskan pada bentang alam kawasan Alas Mertajati dan Danau Tamblingan. Areal yang dipercayai sebagai tempat suci oleh masyarakat adat Catur Desa. Eksploitasi tanah untuk pertanian sayur dan bunga menggunakan pupuk kimia dan pestisida terjadi tanpa kendali dan masif.
Selain itu, menurut Putu Ardana, kondisi sosial masyarakat juga sudah mulai bergeser kian individualis-kapitalistik.
“Petani jadi bermental konsumen, yang terbiasa merengek dan menengadahkan tangan mengharap bantuan pupuk dari pemerintah,” ujarnya pilu.
Padahal, di mata Putu Ardana, petani mesti bermental produsen yang punya harga diri dan gigih memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ia ingin mengembalikan mental petani untuk cerdas memanfaatkan apa yang sudah disediakan alam sekitar secara bijak. Karena semuanya memang sudah tersedia di sana.
“Ada pohon di hutan yang meranggas atau tak tumbuh subur? Siapa yang mupuk?” tanyanya getir.
Putu Ardana mengajak para petani untuk mulai meninggalkan penggunaan pupuk kimia. Karena ada alternatif pupuk kompos atau pupuk dari material organic yang banyak tersedia di lingkungan sekitar.
Tentu saja tidak mudah. Perlu waktu tidak sebentar untuk menemukan cara yang efektif. Hingga ia tiba dengan gagasan mengembalikan Desa Munduk dan sekitarnya sebagai sentra kopi.
Karena tanaman kopi memiliki perakaran yang jauh lebih baik daripada tanaman bunga atau horticultura dalam mengikat tanah. Selain itu, kebun kopi perlu tanaman keras sebagai penaung yang sistem perakarannya juga lebih kokoh dan lebih baik menahan serapan air hujan.
Kopi specialty organic adalah pilihan paling jitu untuk mengajak petani kembali berkebun kopi. Karena harga kopinya yang jauh lebih mahal bisa menjadi pilihan rasional bagi petani untuk beralih dari berkebun sayur dan bunga ke tanaman kopi. Sesungguhnya kopi bisa menjadi media konservasi yang masuk akal, begitu pikirnya. Dari sana lah siasat konservasi Putu Ardana terbersit.
Untuk hasil kopi masuk kategori specialty memang butuh edukasi cara berkebun, merawat, panen, hingga penanganan pasca panen yang lebih baik. Perlu kesabaran ekstra untuk menjalankan siasat ini. Terutama menghadapi penolakan dan keengganan petani hingga mereka mau mempraktikannya.
Hingga saat ini, terhitung sudah tujuh tahun sejak Putu Ardana mulai mengajak petani kembali berkebun kopi Arabica. Kini, jumlah petani yang tertarik berkebun kopi lagi dengan cara baru sudah mulai bertambah.
“Belum banyak, tapi setidaknya sudah ada yang mulai menghitung, hasilnya memang lebih menguntungkan dibandingkan berkebun sayur atau bunga,” ungkap Putu Ardana.
Putu Ardana siap membeli hasil panen kopi dengan harga lebih tinggi. Syaratnya kopi dari kebun yang tidak menggunakan pupuk kimia, tanpa pestisida, dan hanya hasil petik ceri merah saja. Ini memberi kepercayaan diri pada para petani untuk mempraktikan berkebun kopi secara organik.
“Sekarang sudah banyak pembeli dari luar yang beli dengan harga tinggi. Jadi tidak harus dijual ke saya kalau memang ada yang membeli dengan harga lebih baik.” Ucapnya.
“Bagi saya, yang penting mereka mau menanam kopi lagi,” ujarnya sembari tertawa gembira melihat siasat konservasi melalui media berkebun kopi specialty mulai menunjukkan hasil.

Demi semakin mempopulerkan kopi specialty dari wilayah Munduk dan sekitarnya, Putu Ardana membuat brand “Blue Tamblingan”. Nama “Blue Tamblingan” diusulkan Putut EA, seorang teman dari Yogyakarta yang gemar kopi dan sering berkunjung ke Munduk. Penulis sekaligus kepala suku media online Mojok.co ini terinspirasi dari kopi Blue Batak yang eksklusif karena hasil panennya yang terbatas.
Blue Batak adalah kopi Arabica yang ditanam di kebun-kebun kecil yang biasanya berada di belakang rumah para petani di Lintong Nihuta. Sisi Selatan Danau Toba, Sumatera Utara ini memiliki kontur berbukit dengan ketinggian wilayah dan suhu yang ideal untuk tanaman kopi arabica.
Blue Tamblingan juga kopi eksklusif, karena hanya dihasilkan dari lahan di sekitar Danau Tamblingan yang terbatas. Istimewa dengan cita rasa asam jeruk yang lembut dan manis cempedak yang pulen.
Saya melirik kopi tubruk Blue Tamblingan yang masih sisa setengah di atas meja. Saya menyeruputnya hingga memenuhi rongga mulut. Kini cita rasanya tak sebatas menjelajahi indra perasa, tapi membawa jauh menelusuri Alas Mertajati, menerobos lebat pepohonan dan melayang di atas kemilau Danau Tamblingan yang sejuk. Kopi yang berbalut cerita konservasi alam selalu punya cita rasa yang istimewa.
Tak terasa obrolan kami terjeda oleh senyap sesaat. Seperti ada kegalauan yang tiba-tiba mengapung. Sepintas, Putu Ardana tampak melempar pandangannya ke lereng Gunung Sanghyang, jauh di ujung sana, sedikit saja di bawah kaki langit. Tapi pembawaannya yang tenang agaknya cukup berhasil menutupi kegelisahan yang dalam.
“Sekarang kita lagi memperjuangkan pengembalian status Alas Mertajati sebagai hutan adat,” ujarnya, sembari sorot matanya tergesa menuruni cakrawala.
Permohonan sudah didaftarkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun KLHK mewajibkan dipenuhinya sejumlah syarat, salah satunya adalah persetujuan dari Bupati Buleleng.
Putu Ardana bersama masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, saat ini masih menanti tanda tangan dari Bupati Buleleng.
Namun, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana tak kunjung memberikan tanda tangan hingga ia digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Ketut Lihadnyana. Pejabat yang ini pun sama saja, tak ada tanda-tanda mendukung upaya masyarakat adat Catur Desa. Sepertinya harapan itu tampaknya masih jauh dari jangkauan.
Bagi masyarakat adat Catur Desa, Alas Mertajati dan Danau Tamblingan adalah kawasan sakral dan mesti dijaga. Saat ini, dengan status masih sebagai kawasan Taman Wisata Alam membuat hutan seluas 1300 hektar itu rawan dieksploitasi demi mengeruk cuan bisnis pariwisata semata.
Kawasan sumber kehidupan yang mengairi sepertiga Pulau Bali wilayah barat ini mestinya tak boleh dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai.
“Dulu pariwisata timbul sebagai dampak perilaku dan budaya orang Bali. Sekarang jadi sebaliknya, pariwisata dijadikan tujuan utama, budaya dan perilaku orang Bali mesti menyesuaikan,” keluh Putu Ardana dengan nada kesal.
“Kebudayaan dan kesakralan masyarakat Bali dijadikan tontonan pariwisata, seperti pertunjukan topeng monyet,” ujarnya dengan nada keras menahan amarah.

Tapi Putu Ardana tak mau hanya diam dan mengutuki situasi. Apa pun tantangan yang ada di depan, mesti tampak sulit dan berat, harus dihadapi dengan gembira, dan terus melakukan apa yang masih bisa dikerjakan.
Ia bertekad mengajak masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan untuk kembali menempatkan budaya Bali pada martabatnya. Salah satunya dengan menginsiasi terbentuknya Bagaraksa Alas Mertajati (Brasti). Yakni, perkumpulan anak muda yang punya kemauan dan inisiatif menjaga adat dan kelestarian Alas Mertajati.
Anak-anak muda ini sekarang punya militansi sebagai warga masyarakat adat yang mampu melawan stigma sebagai kelompok yang bodoh dan terbelakang. Mereka aktif melakukan pemetaan kawasan Alas Mertajati dan giat mendokumentasikan segala kegiatan budaya.
Putu Ardana juga sedang mempersiapkan pendirian sekolah adat. Sekolah yang lebih banyak mengelaborasi kearifan lokal. Pengajarnya akan lebih banyak dari praktisi di bidangnya yang bisa menjadi fasilitator dalam proses belajar siswa.
Ini bentuk gugatannya pada sistem pendidikan yang cenderung menyeragamkan dan mengelompokkan siswa dalam kategori tertentu. Ia sedang membayangkan sekolah yang memberi keleluasaan siswa belajar dan mendalami passionnya.
Berbagai upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat adat di desanya ini rupanya terdengar oleh sejumlah alumni kampusnya. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, pada 2022, Putu Ardana memperoleh penghargaan “Alumni Mengabdi Awards” dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA).

Matahari kian meninggi, cahayanya mulai menghampiri teras Café Don Biyu.
Putu Ardana mengajak saya menuju salah satu bangunan lain di sisi depan tempat tinggalnya. Ia menunjukkan ruang di mana dirinya biasa meroasting biji kopi yang diolah dari kebun sendiri maupun dari para petani. Mesin roasting produk lokal itu berkapasitas 2 kg per batch. Sayangnya, saat itu mesin sedang rusak.
Hari beranjak siang. Ternyata cukup lama kami mengobrol. Saya berpamitan, tapi sebelumnya tak lupa membeli sekantong kopi Blue Tamblingan. Rencananya, esok hari akan menyertakannya di acara cupping dengan para penggemar kopi di Ubud.
Langit masih cukup cerah, saya memacu sepeda motor tak telalu kencang meninggalkan Desa Munduk. Sesekali gumpalan kabut tebal berduyun-duyun merangsek dari arah danau, menembusi celah pepohonan Alas Mertajati dan kemudian menyelimuti jalanan. Rasanya seperti sedang terbang meniti awan.
Jarak pandang semakin terhalang kabut tebal, saya memutuskan berhenti. Singgah di salah satu balai bengong yang banyak dijumpai di tepi jalan. Menikmati sensasi suasana di atas awan sembari membayangkan, sampai kapan kawasan sakral ini mampu bertahan, dari gempuran banyak kepentingan.
Semoga kopi dan cerita konservasi Danau Tamblingan terus berlanjut bersama Putu Ardana dan generasi muda warga masyarakat adat Catur Desa Dalem Danau Tamblingan.